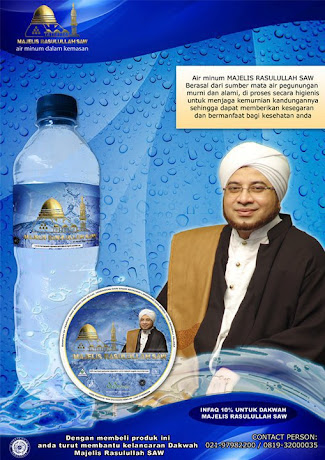(Oleh: Ustadz Abu Asma Kholid Syamhudi)
Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda :
Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allâh,
mereka membacakan kitabullâh dan mempelajarinya,
kecuali turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat menyelimuti mereka,
para malaikat mengelilingi mereka
dan Allâh memuji mereka di hadapan makhluk yang ada didekatnya.
Barangsiapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya.
mereka membacakan kitabullâh dan mempelajarinya,
kecuali turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat menyelimuti mereka,
para malaikat mengelilingi mereka
dan Allâh memuji mereka di hadapan makhluk yang ada didekatnya.
Barangsiapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya.
TAKHRIJ HADITS
Hadits ini merupakan potongan dari hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallâhu'anhu oleh :
- Imam Muslim rahimahullâh, dalam Shahihnya, Kitab Adz Dzikir Wad Du’a, Bab Fadhlul Ijtima’ ‘Ala Tilawatil Qur’an Wa ‘Ala Dzikr, nomor 6793, juz 17/23. (Lihat Syarah An Nawawi).
- Abu Daud rahimahullâh dalam Sunannya, Kitabul Adab, Bab Fil Ma’unah Lil Muslim nomor 4946.
- Ibnu Majah rahimahullâh dalam Sunannya, Muqaddimah, Bab Fadhlul Ulama Wal Hatsu ‘Ala Thalabul Ilmi nomor 225.
BIOGRAFI SINGKAT PERAWI HADITS
Abu Hurairah radhiyallâhu'anhu adalah salah seorang sahabat Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Shahr[1]
Diberi gelar Abu Hurairah karena beliau menyukai seekor kucing yang
dimilikinya. Meskipun baru masuk Islam pada tahun ke tujuh hijriah,
akan tetapi keilmuannya diakui oleh banyak sahabat.
Selama tiga atau empat tahun bersama Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam betul-betul dimanfaatkan oleh beliau. Senantiasa bersama Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam pada saat banyak para shahabat sibuk di pasar atau di tempat yang lain.
Lelaki yang berperangai lembut dengan kulit putih
serta jenggot agak kemerahan ini, sangat gigih menggali ilmu dari
Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam tanpa memperdulikan rasa
lapar yang dialaminya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila beliau
banyak meriwayatkan hadits dari Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi
wasallam.
Hadits dari Abu Hurairah radhiyallâhu'anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullâh dan Imam Muslim rahimahullâh secara bersama sebanyak 326 hadits. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullâh tanpa Imam Muslim rahimahullâh sebanyak 93 hadits dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullâh tanpa Imam Bukhari rahimahullâh 98 hadits.
MAKNA KOSA KATA HADITS
|
Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allâh,
yaitu masjid. Sedangkan madrasah dan tempat-tempat lain yang
mendapatkan keutamaan ini, juga dengan dasar hadits yang
diriwayatkan Imam Muslim rahimahullâh dengan lafadz:

Tidaklah duduk suatu kaum berdzikir kepada Allâh,
kecuali para malaikat mengelilinginya, rahmat menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allâh memujinya di hadapan makhluk yang berada di sisinya. (Riwayat Muslim, no. 6795 dan Ahmad) |
|
ketenangan |
|
diselimuti rahmat Allâh |
|
dikelilingi malaikat rahmah |
|
|
Allâh memuji dan memberikan pahala di hadapan para malaikatNya. |
|
siapa yang kurang amalannya tidak akan mencapai martabat orang yang beramal sempurna, walaupun memiliki nasab ulama. |
FAIDAH HADITS
Pertama: Arti Penting Majelis Ilmu
Majelis ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari para ulama rabbani. Bahkan mengadakan majelis ilmu merupakan
perkara penting yang harus dilakukan oleh seorang ‘alim. Karena hal
itu merupakan martabat tertinggi para ulama rabbani, sebagaimana
firman Allâh Ta'âla :

Tidak wajar bagi seseorang manusia
yang Allâh berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian,
lalu dia berkata kepada manusia,
”Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allâh”.
Akan tetapi (dia berkata),
”Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,
karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab
dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
(QS Ali Imran:79)
yang Allâh berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian,
lalu dia berkata kepada manusia,
”Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allâh”.
Akan tetapi (dia berkata),
”Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,
karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab
dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
(QS Ali Imran:79)
Hal inipun dilakukan Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam. Beliau shallallâhu 'alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menghadiri majelis ilmu dengan sabdanya :

Jika kalian melewati taman syurga maka berhentilah.
Mereka bertanya, ”Apakah taman syurga itu?”
Beliau menjawab, ”Halaqoh dzikir (majlis Ilmu)."
(Riwayat At Tirmidzi
dan dishahihkan Syeikh Salim bin Ied Al Hilali
dalam Shahih Kitabul Adzkar 4/4)
Mereka bertanya, ”Apakah taman syurga itu?”
Beliau menjawab, ”Halaqoh dzikir (majlis Ilmu)."
(Riwayat At Tirmidzi
dan dishahihkan Syeikh Salim bin Ied Al Hilali
dalam Shahih Kitabul Adzkar 4/4)
Demikian juga para salafush shalih sangat bersemangat mengadakan dan menghadirinya. Oleh karena itu kita dapatkan riwayat tentang majelis ilmu mereka. Di antaranya majelis Abdillâh bin Mas’ud di Kufah, Abu Hurairah di Madinah, Imam Malik di masjid Nabawi, Syu’bah bin Al Hajjaj, Yazid bin Harun, Imam Syafi’i, Imam Ahmad di Baghdad, Imam Bukhari dan yang lainnya.
Kedua: Faidah dan Keutamaan Majelis Ilmu.
Di antara faidah majelis ilmu ialah :
- Mengamalkan perintah Allâh Ta'âla dan Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam dan mencontoh jalan hidup para salafush shalih.
- Mendapatkan ketenangan.
- Mendapatkan rahmat Allâh Ta'âla .
- Dipuji Allâh di hadapan para malaikat.
- Mengambil satu jalan mendapatkan warisan para Rasul.
- Mendapatkan ilmu dan adab dari seorang alim.
Ketiga. Adab Majelis Ilmu.
Perkara yang harus diperhatikan dan dilakukan agar dapat mengambil faidah dari majelis ilmu ialah :
| Ikhlas. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Hendaklah kepergian dan duduknya
seorang penuntut ilmu ke majelis ilmu, hanya karena Allâh
semata. Tanpa disertai riya’ dan keinginan dipuji orang lain.
Seorang penuntut ilmu hendaklah bermujahadah dalam meluruskan
niatnya. Karena ia akan mendapatkan kesulitan dan kelelahan dalam
meluruskan niatnya tersebut. Oleh karena itu Imam Sufyan
Ats Tsauri berkata:
“Saya tidak merasa susah dalam meluruskan sesuatu melebihi niat.”[2]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bersemangat menghadiri majelis ilmu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kesungguhan dan semangat yang tinggi
dalam menghadiri majelis ilmu tanpa mengenal lelah dan
kebosanan sangat diperlukan sekali. Janganlah merasa cukup dengan
menghitung banyaknya. Akan tetapi hitunglah berapa besar dan banyaknya
kebodohan kita. Karena kebodohan sangat banyak, sedangkan ilmu
yang kita miliki hanya sedikit sekali.
Lihatlah kesemangatan para ulama
terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Abul Abbas Tsa’lab
rahimahullâh, seorang ulama nahwu berkomentar tentang Ibrahim
Al Harbi rahimahullâh:
“Saya tidak pernah kehilangan Ibrahim Al
Harbi dalam majelis pelajaran nahwu atau bahasa selama
lima puluh tahun”.
Lantas apa yang diperoleh Ibrahim Al
Harbi? Akhirnya beliau menjadi ulama besar dunia. Ingatlah, ilmu
tidak didapatkan seperti harta waris. Akan tetapi dengan
kesungguhan dan kesabaran.
Alangkah indahnya ungkapan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullâh :
“Ilmu adalah karunia
yang diberikan Allâh kepada orang yang disukainya. Tidak ada
seorangpun yang mendapatkannya karena keturunan. Seandainya
didapat dengan keturunan, tentulah orang yang paling
berhak ialah ahli bait Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam ”.
Demikian juga Imam Malik rahimahullâh, ketika melihat
anaknya yang bernama Yahya keluar dari rumahnya bermain :
“Alhamdulillâh, Dzat yang tidak menjadikan ilmu ini seperti harta waris”.
Abul Hasan Al Karkhi rahimahullâh berkata :
“Saya hadir di majelis
Abu Khazim pada hari Jum’at walaupun tidak ada
pelajaran, agar tidak terputus kebiasanku menghadirinya”.
Lihatlah semangat mereka dalam mencari ilmu dan
menghadiri majelis ilmu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan
hasil yang menakjubkan.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat, bahkan harus mendahuluinya dari selainnya. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Seseorang bila terbiasa bersegera dalam
menghadiri majelis ilmu, maka akan mendapatkan faidah yang sangat
banyak. Sehingga Asysya’bi rahimahullâh ketika ditanya :
“Dari mana engkau mendapatkan ilmu ini semua?”
Beliau menjawab :
“Tidak bergantung kepada
orang lain. Bepergian ke negeri-negeri dan sabar seperti
sabarnya keledai, serta bersegera seperti bersegeranya
elang”.[3]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak dapat dihadirinya.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Terkadang seseorang tidak dapat
menghadiri satu majelis ilmu karena alasan tertentu, seperti
sakit dan yang lainnya. Sehingga tidak dapat memahami
pelajaran yang ada dalam majelis tersebut. Dalam keadaan seperti
ini hendaklah ia mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang
terlewatkan itu. Karena sifat pelajaran itu seperti rangkaian.
Jika hilang darinya satu bagian, maka dapat mengganggu yang
lainnya.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mencatat faidah-faidah yang didapatkan dari kitab. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mencatat faidah pelajaran dalam kitab
tersebut atau dalam buku tulis khusus. Faidah-faidah ini akan
bermanfaat jika dibaca ulang dan dicatat dalam mempersiapkan
materi mengajar, ceramah dan menjawab permasalahan. Oleh karena
itu sebagian ahli ilmu menasihati kita. Jika membeli sebuah buku,
agar tidak memasukkannya ke perpustakaan, kecuali setelah
melihat kitab secara umum. Caranya dengan mengenal penulis dan
pokok bahasan yang terkandung dalam kitab dengan melihat daftar
isi dan membaca (sesuai dengan kecukupan waktu) sebagian pokok
bahasan kitab.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ini termasuk adab yang penting dalam
majelis ilmu. Imam Adz Dzahabi rahimahullâh menyampaikan kisah
Ahmad bin Sinan, ketika beliau berkata :
“Tidak ada
seorangpun yang bercakap-cakap di majelis Abdurrahman bin
Mahdi. Suara pena tidak terdengar. Tidak ada yang bangkit,
seakan-akan di kepala mereka ada burung atau seakan-akan mereka
berada dalam shalat”.[4]
Dan dalam riwayat yang lain:
“Jika beliau
melihat seseorang dari mereka tersenyum atau berbicara, maka
dia mengenakan sandalnya dan keluar”.[5]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tidak boleh berputus asa. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Terkadang sebagian kita telah hadir di
suatu majelis ilmu dalam waktu yang lama. Akan tetapi tidak
dapat memahaminya kecuali sedikit sekali. Lalu timbul dalam
diri kita perasaan putus asa dan tidak mau lagi duduk disana.
Tentunya hal ini tidak boleh terjadi. Karena telah dimaklumi,
bahwa akal dan kecerdasan setiap orang berbeda. Kecerdasan
tersebut akan bertambah dan berkembang karena dibiasakan.
Semakin sering seseorang membiasakan
dirinya, maka semakin kuat dan baik kemampuannya. Lihatlah
kesabaran dan keteguhan para ulama dalam menuntut ilmu dan
mencari jawaban satu permasalahan! Lihatlah apa yang dikatakan
Syeikh Muhammad Al Amin Asy Syinqiti, “Ada satu masalah yang
belum saya pahami. Lalu saya kembali ke rumah dan saya meneliti
dan terus meneliti. Sedangkan pembantuku meletakkan
lampu atau lilin di atas kepala saya. Saya terus meneliti dan
minum teh hijau sampai lewat 3/4 hari, sampai terbit fajar hari
itu”. Kemudian beliau berkata,“Lalu terpecahlah problem
tersebut”. Lihatlah bagaimana beliau menghabiskan harinya dengan
meneliti satu permasalahan yang belum jelas baginya.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Jangan memotong pembicaraan guru atau penceramah | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Termasuk adab yang harus diperhatikan
dalam majelis ilmu yaitu tidak memotong pembicaraan guru
atau penceramah. Karena hal itu termasuk adab yang jelek.
Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan
sabdanya :

Tidak termasuk golongan kami
orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. (Riwayat Ahmad dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’)
Imam Bukhari rahimahullâh menulis di Shahihnya, orang
yang ditanya satu ilmu dalam keadaan sibuk berbicara,
hendaknya menyempurnakan pembicaraannya. Kemudian menyampaikan
hadits:

Dari Abu Hurairah, beliau berkata,
“Ketika Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam berada di majelis menasihati kaum, datanglah seorang A’rabi dan bertanya : ”Kapan hari kiamat?” (Tetapi) beliau terus saja berbicara sampai selesai. Lalu (Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam) bertanya : “Mana tampakkan kepadaku yang bertanya tentang hari kiamat?” Dia menjawab: ”Saya, wahai Rasûlullâh.” Lalu beliau berkata: “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat”. Dia bertanya lagi: “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau menjawab: “Jika satu perkara diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat”. (Riwayat Bukhari)
Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam dalam hadits ini berpaling dan tidak memperhatikan penanya untuk mendidiknya.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Beradab dalam bertanya | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Bertanya adalah kunci ilmu. Juga diperintahkan Allâh Ta'âla dalam firmanNya:
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui. (QS An Nahl/16 : 43)
Demikian pula Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam
mengajarkan, bahwa obat kebodohan yaitu dengan bertanya,
sebagaimana sabda beliau:
Tidakkah mereka bertanya, ketika mereka tidak tahu?
Sesungguhnya obat ketidak mengertian adalah bertanya. (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi dan dishahihkan Syeikh Salim Al Hilali dalam Tanqihul Ifadah Al Muntaqa Min Miftah Daris Sa’adah, hal. 174)
Imam Ibnul Qayim rahimahullâh berkata:
”Ilmu memiliki enam
martabat. Yang pertama, baik dalam bertanya …… Ada di antara
manusia yang tidak mendapatkan ilmu, karena tidak baik dalam
bertanya. Adakalanya, karena tidak bertanya langsung. Atau
bertanya tentang sesuatu, padahal ada yang lebih penting. Seperti
bertanya sesuatu yang tidak merugi jika tidak tahu dan
meninggalkan sesuatu yang mesti dia ketahui.”[6]
Demikian juga Al Khathib Al Baghdadi rahimahullâh memberikan pernyataan:
”Sepatutnyalah rasa malu tidak menghalangi seseorang dari bertanya tentang kejadian yang dialaminya.”[7]
Oleh karena itu perlu dijelaskan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bertanya, diantaranya:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mengambil akhlak dan budi pekerti guru. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tujuan hadir di majelis ilmu, bukan hanya
terbatas pada faidah keilmuan semata. Ada hal lain yang juga
harus mendapat perhatian serius. Yaitu melihat dan mencontoh
akhlak guru.
Demikianlah para ulama terdahulu. Mereka
menghadiri majelis ilmu, juga untuk mendapatkan akhlak dan budi
pekerti seorang ‘alim. Untuk dapat mendorong mereka
berbuat baik dan berakhlak mulia.
Diceritakan oleh sebagian ulama, bahwa majelis
Imam Ahmad dihadiri lima ribu orang. Dikatakan hanya lima
ratus orang yang menulis, dan sisanya mengambil faidah dari
tingkah laku, budi pekerti dan adab beliau.[9]
Abu Bakar Al Muthaawi’i rahimahullâh berkata:
“Saya menghadiri
majelis Abu Abdillâh –beliau mengimla’ musnad kepada
anak-anaknya– duabelas tahun. Dan saya tidak menulis, akan
tetapi saya hanya melihat kepada adab dan akhlaknya”.[10]
Dengan demikian kehadiran kita dalam majelis ilmu, hendaklah bukan semata-mata mengambil faidah ilmu saja, akan tetapi juga mengambil semua faidah yang ada. |
Inilah sebagian faidah yang dapat diambil dari hadits ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
| [1] | Para ulama’ berbeda pendapat mengenai nama asli beliau. Pendapat terkuat, beliau bernama Abdurrahman bin Shahr |
| [2] | Lihat Tadzkiratus Sami’ wal Mutakallim, hal.68. |
| [3] | Lihat Rihlah Fi Thalabil Hadits, hal.196. |
| [4] | Tadzkiratul Hufadz 1/331 |
| [5] | Siyar A’lam Nubala 4/1470. |
| [6] | Miftah Daris Sa’adah 1/169. |
| [7] | Al Faqiih Wal Mutafaaqih 1/143. |
| [8] | Jami’ Bayanil Filmi Wa Fadhlihi 2/136. |
| [9] | Siyar A’lam Nubala 11/316. |
| [10] | Ibid. 11/316 |
(Majalah As-Sunnah Edisi 08/Tahun VI)